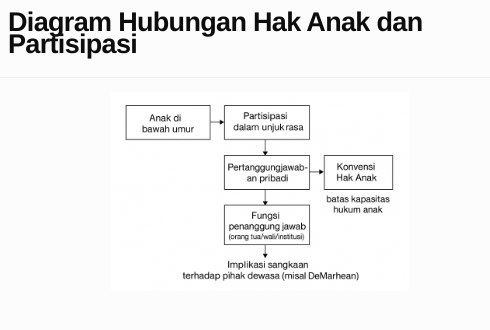Proses menjadi dan menyandang prediket manusia
Karam (Sebatas Monolog Usang)
Senin, 12 Mei 2025 14:12 WIB
Menyoal hidup dalam dunia yang untuk "menjadi" sesuatu, tanpa pernah memberinya kesempatan untuk memahami apa itu menjadi sejati
Di balik keramaian yang menggema di permukaan, di dalam ruang sunyi yang dipenuhi bayang-bayang, ada pergulatan yang lebih dalam. Bukanlah sekadar soal takdir atau keberuntungan, tetapi tentang bagaimana kita hidup dalam dunia yang terus menuntut kita untuk "menjadi" sesuatu, tanpa pernah memberinya kesempatan untuk memahami apa itu menjadi sejati.
***
Aku pernah ditawari persahabatan. Tapi dengan satu syarat. Aku harus membawa pikiranku, dan meninggalkan tempat tidur serta altar persembahanku.
Mereka tak tahu: tempat tidurku adalah kehendak liar tempat aku merayakan hidup yang tak tunduk pada dogma; dan altarku bukan tempat ibadah, melainkan bara dendam pada ilusi suci yang meninabobokan manusia.
Aku tidak datang sebagai teman setengah matang. Bila aku datang, aku datang dengan luka, murka, dan tawa yang menggugat. Aku tak tahu cara berlutut, bahkan pada yang kucintai. Aku hanya tahu berjalan bersama, jika langkah itu menuju medan liar, bukan panggung sandiwara. Dan kini, aku berjalan di tanah, milik sebuah negeri yang katanya subur, tapi akarnya diracuni benalu kekuasaan. Negeri yang hangat di luar, tapi menyimpan luka di perut buminya.
Aku tak datang sebagai pelancong. Aku datang sebagai api. Bukan untuk menghangatkan, tapi untuk membakar. kaupun tahu, di negeri ini, eksistensi manusia telah tergadai oleh ekstasi digital. Mereka tidak dijinakkan oleh dogma tua, melainkan oleh layar yang lebih adiktif daripada iman. Mereka menari di TikTok, bukan di jalan perlawanan. Mereka tersenyum dalam filter, dan membusuk dalam diam.
Tak ada lagi borgol. Yang ada hanya candu validasi. Likes menggantikan makna. Views menggantikan visi. Mereka tidak mengemis roti, tapi perhatian. Dunia ini bukan lagi ladang perjuangan. Ia telah berubah menjadi panggung narsisme masal, di mana yang mengingatkan disebut iri, dan yang menggugat dianggap gila.
Tapi aku tetap berjalan. Menyusuri sekolah-sekolah tempat anak-anak dipaksa menghafal, bukan berpikir. Kantor-kantor tempat mimpi ditukar dengan absen pagi. Rumah-rumah ibadah tempat langit dijual dengan harga ketaatan.
Aku ingin berteriak, tapi suara itu hanya berputar dalam rongga dada. Sebab di luar, tak ada yang mendengar. Atau mereka sudah terlalu lama hidup dalam kebisingan, hingga kebenaran terdengar seperti gangguan.
Yang paling memuakkan bukan kebusukan kekuasaan, tapi keretakan dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang tak bisa bersosialisasi. Yang saling mencurigai. Yang menjadikan konflik sebagai cara untuk merasa hidup. Ego mereka adalah tuan. Pikiran keliru mereka adalah kompas. Bahkan dalam bertetangga pun, mereka gagal mengenali wajah kemanusiaan.
Aku ingin membakar panggung. Tapi apinya tak pernah ada. Yang kupunya hanya cermin kaca, memantulkan sinar surya. Aku bertanya, apakah pantulan bisa membakar? Aku tak tahu. Tapi itu satu-satunya senjata yang tersisa. Maka aku gunakan itu. Bukan untuk melihat diriku; tapi untuk membutakan mereka yang terlalu lama hidup dalam gelap.
Namun dunia tak bodoh. Ia tidak menyerang langsung padaku. Ia mengarahkan senjata ke mereka yang kucintai. Setiap bara yang kubakar, diarahkan balasannya pada keluarga. Ancaman yang paling licik: membungkamku dengan cinta. Membuatku diam bukan karena takut, tapi karena tak tega.
Dunia yang disebut beradab ini telah menemukan cara paling sunyi untuk membunuh: menjadikan cinta sebagai rantai. Bukan aku yang ditembak, tapi orang-orang terdekatku. Mereka ingin membuatku percaya bahwa keberanianku adalah kejahatan.
Aku bukan takut mati. Tapi aku tahu, bila aku meledak, serpihannya bukan hanya mengenai musuh. Ia bisa melukai rumah. Bisa mematahkan tulang mereka yang tak salah. Maka aku bertahan. Bukan karena aku lemah. Tapi karena aku masih mencintai.
Dan kini aku berada di ambang. Di batas antara nyala dan kasih. Di antara api yang tak bisa padam, dan cinta yang tak bisa kukhianati. Maka aku putuskan: aku tak akan jadi penyair kematian peradaban ini. Tapi aku juga belum akan membakar panggungnya.
Aku memilih menjadi asap. Tak bisa dipegang, tapi menyesakkan. Tak bisa dibungkam, tapi menyusup ke setiap ruang sempit. Aku akan jadi bisikan, bukan teriakan. Aku akan menyelinap, bukan menabrak. Aku akan jadi racun pelan dalam sistem yang busuk ini.
Aku tidak perlu jadi siapa-siapa. Aku hanya akan menjadi. Menjadi luka yang jujur. Menjadi perlawanan yang diam. Menjadi nyala kecil yang menunggu angin datang, bukan untuk padam, tapi untuk meledak.
Sebab jika dunia memaksaku memilih antara jadi api atau jadi abunya; aku akan jadi asap. Yang tak terlihat, tapi membuat langit tak lagi biru. Yang tak tertangkap, tapi membuat kekuasaan sesak napas. Yang tidak dibanggakan, tapi tak bisa dilupakan.
(...)
Penulis Indonesiana
1 Pengikut

Karam (Sebatas Monolog Usang)
Senin, 12 Mei 2025 14:12 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler


 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0








 99
99 0
0